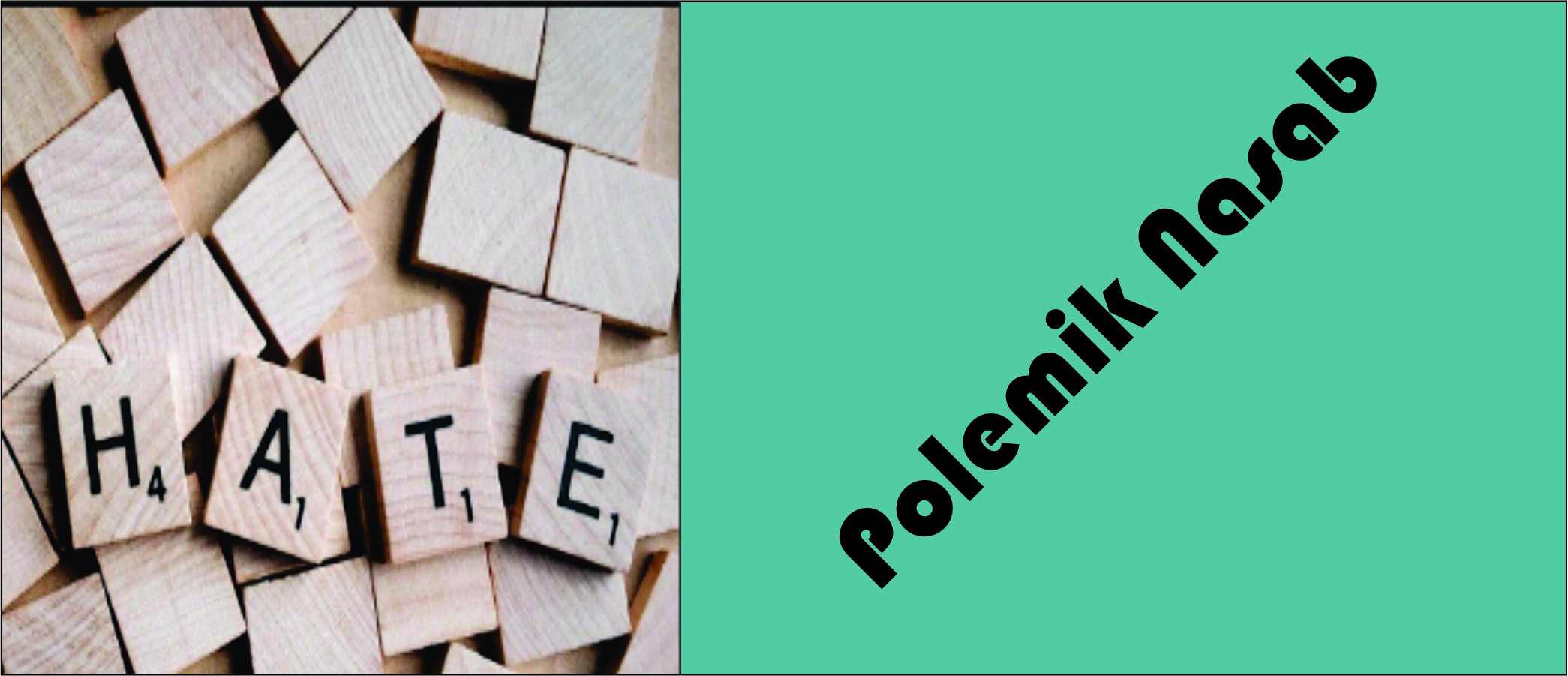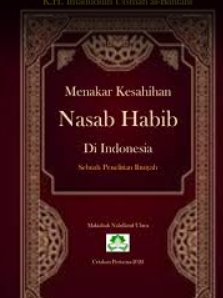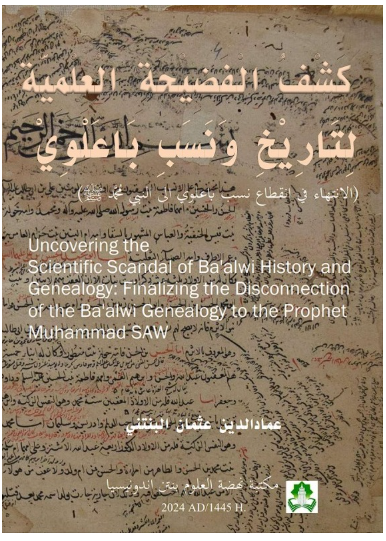Sejarah politik Indonesia mencatat perjuangan panjang melawan feodalisme yang dianggap sebagai hambatan terhadap kemajuan dan persatuan bangsa. Dalam konteks ini, gelar-gelar feodal seperti Habib sering kali menjadi sorotan karena dianggap tidak hanya berfungsi sebagai simbol status sosial, tetapi juga sebagai alat untuk memengaruhi masyarakat. Dua presiden besar Indonesia, Soekarno dan Soeharto, mengambil langkah-langkah konkret untuk membatasi penggunaan gelar-gelar semacam itu melalui regulasi hukum. Namun, dinamika ini mengalami perubahan besar di era reformasi, yang membawa kebebasan berekspresi lebih luas.
Pada masa awal kemerdekaan, Soekarno menghadapi tantangan besar dalam menyatukan bangsa yang baru saja terlepas dari belenggu kolonialisme. Salah satu ancaman utama yang ia identifikasi adalah feodalisme, yang dianggapnya sebagai residu masa penjajahan dan penghalang bagi semangat nasionalisme. Untuk itu, ia menerapkan kebijakan yang tegas:
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946: Regulasi ini melarang penggunaan gelar feodal, termasuk Habib, untuk tujuan politik, sosial, atau keagamaan. Langkah ini bertujuan untuk menghapus hierarki sosial yang bertentangan dengan semangat egalitarianisme.
- Dekrit Presiden Tahun 1959: Keputusan ini mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar hukum negara dan melarang simbol-simbol feodal dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Soekarno, feodalisme bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi Indonesia yang menekankan kesetaraan dan persatuan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1959: Regulasi ini mempertegas larangan penggunaan gelar feodal, termasuk dalam dokumen resmi seperti KTP dan akta kelahiran. Soekarno ingin memastikan bahwa identitas nasional tidak terkotori oleh pengaruh feodalisme.
Ketika Soeharto mengambil alih kepemimpinan, ia mewarisi semangat anti-feodalisme dari pendahulunya. Namun, pendekatan Soeharto lebih pragmatis, dengan fokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, ia melanjutkan pembatasan penggunaan gelar feodal melalui kebijakan berikut:
- Keputusan Presiden Nomor 241/1966: Kebijakan ini bertujuan untuk memberantas feodalisme dan praktik-praktik klenik yang dianggap menghambat modernisasi.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 47/1966: Peraturan ini melarang penggunaan gelar feodal dalam dokumen resmi. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah pengaruh klan tertentu dalam kehidupan sosial dan politik.
Di era Orde Baru, regulasi-regulasi ini menjadi bagian dari strategi besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih homogen dan terintegrasi. Namun, langkah-langkah tersebut juga menuai kritik karena dianggap mengekang kebebasan berekspresi dan mengabaikan aspek budaya tertentu.
Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam struktur politik dan sosial Indonesia. Kebebasan berekspresi yang lebih luas memungkinkan masyarakat untuk kembali mengekspresikan identitas budaya dan keagamaannya. Dalam konteks ini, penggunaan gelar Habib meningkat secara signifikan.
Tokoh seperti Habib Rizieq Shihab muncul sebagai simbol kebangkitan identitas keagamaan di Indonesia. Sebagai pendiri Front Pembela Islam (FPI), ia memanfaatkan gelar Habib untuk membangun pengaruh dan menghimpun dukungan dari umat Islam. Di sisi lain, fenomena ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kebangkitan identitas keagamaan dapat memicu segregasi sosial dan melemahkan semangat nasionalisme.
Selain Habib Rizieq, tokoh lain seperti Lutfi bin Yahya juga memainkan peran penting dalam dinamika ini. Lutfi bin Yahya tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai sosok yang berhasil meraih posisi strategis dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Ia mengambil alih peran penting dalam NU melalui jabatan Ketua Majelis Ulama Jawa Tengah dan Ketua Badan Otonom NU JATMAN (Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah). Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk memperkuat pengaruh komunitasnya di tingkat nasional sekaligus memperluas pengaruh politik dan sosial di kalangan umat Islam.
Kebangkitan identitas keagamaan di era reformasi memunculkan dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, kebebasan berekspresi merupakan salah satu pencapaian terbesar reformasi. Namun, di sisi lain, penguatan simbol-simbol feodal seperti gelar Habib dapat menciptakan kesenjangan sosial dan mengancam persatuan nasional.
Pelajaran dari era Soekarno dan Soeharto menunjukkan pentingnya regulasi yang seimbang. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan untuk mempromosikan agenda politik atau segregasi sosial. Dalam konteks ini, dialog antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan dan kesetaraan.
Fenomena penggunaan gelar Habib di Indonesia mencerminkan dinamika yang kompleks antara budaya, agama, dan politik. Langkah-langkah Soekarno dan Soeharto dalam membatasi feodalisme adalah upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara dan nasionalis. Namun, era reformasi menunjukkan bahwa kebijakan semacam itu perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Sebagai bangsa yang beragam, Indonesia perlu terus mengupayakan keseimbangan antara pengakuan identitas budaya dan menjaga persatuan nasional. Dengan belajar dari sejarah, kita dapat membangun masa depan yang lebih inklusif dan harmonis.
Ditulis oleh : @Syaf